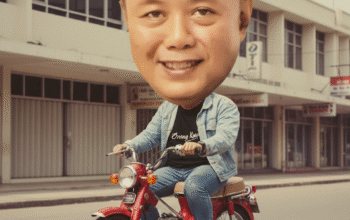Jurnalekbis.com , Opini – Rasanya sungguh membanggakan bisa menjadi bagian dari bangsa besar ini. Bangsa yang lahir dari keberanian, dipelihara oleh pengorbanan, dan terus berjalan dengan penuh harapan. Kita boleh berbeda bahasa, suku, agama, dan budaya, tetapi di bawah satu bendera, kita adalah keluarga besar Indonesia. Sebuah rumah yang selalu kita rindukan, meski penuh tantangan dan masalah.
Dalam setiap perayaan kemerdekaan, ada rasa haru yang tidak bisa disembunyikan. Kita mengingat jasa para pahlawan yang berjuang tanpa pamrih, kita mengenang air mata ibu-ibu yang melepas anaknya ke medan perang, dan kita belajar dari semangat gotong royong yang menjadi napas bangsa ini. Karena itu ucapan teriring doa, semoga Indonesia terus kuat, adil, dan menjadi rumah yang membanggakan bagi generasi mendatang.
Delapan puluh tahun yang lalu, Indonesia lahir dengan pekik merdeka. Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah bangsa yang menegaskan bahwa rakyat negeri ini tidak lagi tunduk pada penjajahan asing. Namun, di usia 80 tahun ini, pertanyaan besar menggema: apakah kita benar-benar sudah merdeka sepenuhnya, atau sekadar menikmati kemerdekaan yang setengah hati?
Jika merdeka dimaknai sekadar bebas dari kolonialisme, maka jawabannya jelas: ya. Namun, jika merdeka berarti terbebas dari kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, ketergantungan, dan penindasan dalam wajah baru, maka jawabannya: belum. Di sinilah refleksi 80 tahun ini menjadi penting, karena kemerdekaan sejati selalu lahir dari proses panjang, bukan sekadar deklarasi.
Data terbaru BPS menunjukkan bahwa sekitar 9,2% rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini memang menurun dibanding era sebelumnya, tetapi tidak bisa menutupi fakta bahwa jutaan orang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Di saat bersamaan, jurang ketimpangan semakin melebar. Segelintir orang menguasai porsi besar kekayaan nasional, sementara banyak anak muda kesulitan mengakses pendidikan tinggi.
Pendidikan, yang seharusnya menjadi jalan menuju kemerdekaan intelektual, justru tertinggal. Angka partisipasi pendidikan tinggi kita hanya sekitar 32%, jauh tertinggal dari Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam. Hal ini menandakan bahwa cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa masih menghadapi jalan panjang. Bagaimana mungkin kita bisa bersaing di era global jika sumber daya manusia tidak dipersiapkan secara serius?
Di sisi lain, ancaman terhadap demokrasi semakin nyata. Kontroversi tentang rencana peluncuran buku sejarah “resmi” 10 jilid yang ditunda, karena dituding menutup-nutupi peristiwa kelam bangsa seperti tragedi 1965 dan Mei 1998, memperlihatkan betapa rentannya kebebasan intelektual. Sejarah adalah ingatan kolektif. Jika ingatan itu dihapus, maka kita kehilangan arah dalam membaca masa depan.
Ironisnya, di tengah narasi “penyatuan sejarah” itu, masyarakat justru melawan dengan simbol-simbol budaya populer. Viral bendera bajak laut One Piece yang dikibarkan di tengah momentum kemerdekaan menjadi bentuk protes simbolik. Sebagian masyarakat menggunakannya untuk menyindir elit yang dianggap serakah, korup, dan jauh dari rakyat. Fenomena ini menunjukkan bahwa generasi muda memilih bahasa baru untuk menyuarakan keresahan.
Meski diperdebatkan, aksi simbolik itu menggambarkan keresahan mendalam: kemerdekaan telah digadaikan pada kepentingan elit dan oligarki. Seakan-akan bangsa ini merdeka hanya di atas kertas, sementara rakyat masih menjadi “penonton” dalam panggung pembangunan yang dikendalikan segelintir orang. Kemerdekaan tanpa keadilan hanyalah slogan kosong.
Selain masalah demokrasi, kerusakan lingkungan juga menjadi ironi besar. Indonesia kini dijuluki sebagai salah satu “tong sampah global”, karena menerima impor limbah plastik senilai ratusan juta dolar. Di berbagai daerah, tambang menggerus ruang hidup masyarakat lokal, sementara regulasi lingkungan justru dilonggarkan atas nama investasi. Padahal, para pejuang bangsa dahulu memperjuangkan tanah air ini bukan untuk dirusak demi keuntungan sesaat.

Refleksi 80 tahun kemerdekaan harus berani menyorot isu kedaulatan ekologis. Kemerdekaan sejati bukan hanya kedaulatan politik, melainkan juga keberanian menjaga bumi, hutan, laut, dan tanah agar tetap lestari. Bagaimana kita bisa menyebut diri merdeka, jika air kotor, udara tercemar, tanah longsor, dan masyarakat adat terusir dari tanah leluhur mereka?
Dalam hal pangan, kemandirian pun masih jauh dari harapan. Harga jagung, beras, hingga daging sering kali melambung tinggi, dipengaruhi kartel dan impor. Rakyat kecil kembali menjadi korban. Padahal, amanat Pasal 33 UUD 1945 jelas: bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kenyataannya, lebih sering untuk kemakmuran segelintir pengusaha besar.
Demokrasi yang kita banggakan pun kian redup. Pemilu masih dihantui politik uang, praktik dinasti politik, dan pembungkaman kritik. Ruang publik yang seharusnya dipenuhi diskusi sehat kini kerap menjadi ajang polarisasi, hoaks, dan propaganda. Kebebasan berpendapat yang dulu diperjuangkan dengan darah, kini terancam oleh kepentingan jangka pendek.
Media sosial memang membuka ruang baru, tetapi sekaligus menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ia memberi kesempatan rakyat untuk bersuara. Di sisi lain, ia dipenuhi noise, kebencian, dan manipulasi informasi. Dalam situasi seperti ini, kemerdekaan intelektual dan literasi digital menjadi tantangan nyata bagi bangsa.
Delapan puluh tahun merdeka juga memberi kita peluang untuk bertanya: apakah pembangunan ekonomi yang digembar-gemborkan benar-benar berpihak pada rakyat? Hilirisasi tambang, investasi asing, dan pembangunan infrastruktur memang meningkatkan angka pertumbuhan, tetapi siapa yang paling merasakan manfaatnya? Apakah rakyat desa, petani, nelayan, dan buruh, ataukah para konglomerat dan investor besar?
Sejarah mencatat, bangsa ini lahir dari keberanian melawan penjajahan. Kini, penjajahan hadir dalam wajah baru: kapitalisme global, ketergantungan impor, dan dominasi modal asing. Jika kita tidak berhati-hati, kita hanya akan menjadi penonton dalam panggung ekonomi dunia. Merdeka, tapi tanpa kedaulatan.
Namun, meski banyak ironi, bangsa ini tetap memiliki harapan. Semangat generasi muda untuk bersuara melalui budaya pop, seni, literasi digital, hingga gerakan lingkungan, menunjukkan bahwa api kemerdekaan belum padam. Mereka mencari cara baru untuk memperjuangkan keadilan dan keberlanjutan, meski berbeda dengan cara generasi sebelumnya.
Kemerdekaan di usia 80 ini harus kita maknai sebagai momentum untuk menyatukan kembali visi kebangsaan. Visi yang tidak berhenti pada seremoni dan lomba tujuhbelasan, tetapi menjelma menjadi kebijakan nyata: mengurangi kemiskinan, meratakan pendidikan, memperkuat demokrasi, menjaga lingkungan, dan menegakkan keadilan sosial.
Refleksi ini juga harus menjadi tamparan bagi elit politik. Jangan jadikan kemerdekaan sekadar panggung pidato penuh janji, sementara rakyat menunggu bukti nyata. Bangsa ini butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan strategis untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk segelintir orang.
80 tahun merdeka adalah usia matang. Sudah seharusnya bangsa ini lebih dewasa dalam mengelola perbedaan, lebih bijak dalam mengelola sumber daya, dan lebih berani dalam melawan ketidakadilan. Jika tidak, kita akan terus terjebak dalam lingkaran “kemerdekaan setengah hati”.
Tentu, tantangan ini tidak ringan. Tetapi justru di situlah nilai dari kemerdekaan: ia bukan hadiah, melainkan amanah. Amanah yang harus dijaga dengan keberanian, kejujuran, dan pengorbanan. Sama seperti para pendiri bangsa yang rela mempertaruhkan nyawa demi sebuah cita-cita.
Maka, refleksi 80 tahun kemerdekaan bukan sekadar mengulang pekik merdeka, melainkan menanyakan kembali: apakah kita sungguh merdeka? Jawaban itu bukan ada di spanduk, bukan di pidato, bukan di lomba panjat pinang, melainkan di keseharian rakyat: apakah mereka bisa hidup layak, berpendidikan, bebas bersuara, dan menjaga bumi yang diwariskan untuk generasi berikutnya. Jika jawabannya belum, maka tugas kita masih panjang: melanjutkan perjuangan agar kemerdekaan benar-benar utuh, adil, dan berkelanjutan.