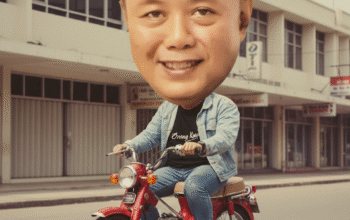Jurnalekbis.com- Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menampilkan dua wajah yang kontras: wajah survei dan wajah realitas. Di layar media, hasil jajak pendapat menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tinggi Poltracking mencatat 78,1 persen rakyat puas, sementara Indeks Politica menempatkan angkanya lebih tinggi, 83,5 persen. Namun, di saat yang sama, lembaga riset Celios justru memberi nilai 3 dari skala 10, menggambarkan penilaian jurnalis terhadap kinerja pemerintah yang masih jauh dari memuaskan. Dua angka yang sama-sama benar, tetapi berbicara dari dunia yang berbeda: yang satu berbicara tentang persepsi, yang lain tentang pengamatan.
Dalam konteks demokrasi modern, survei seringkali menjadi alat ukur legitimasi politik. Ia bisa menjadi penopang citra, sekaligus pengalih perhatian publik. Ketika angka-angka kepuasan dirayakan tanpa kritik, ia berpotensi berubah menjadi propaganda yang menutupi realitas lapangan. Sebab di balik euforia statistik itu, masih terhampar deret panjang persoalan: harga beras yang naik, ketimpangan ekonomi yang melebar, serta pelanggaran kebebasan sipil yang masih terjadi. Kepuasan publik dalam survei tidak selalu mencerminkan kesejahteraan rakyat di lapangan; sering kali ia hanyalah ilusi stabilitas yang dipoles oleh narasi politik.
Perbedaan hasil antara Celios dan Poltracking tidak semata soal metodologi, tetapi mencerminkan perbedaan kelas sosial dan perspektif epistemik. Survei Celios melibatkan jurnalis mereka yang mengamati langsung dinamika kebijakan, konflik kepentingan, dan narasi kekuasaan di balik layar. Sementara survei Poltracking dan Indeks Politica mewakili persepsi masyarakat umum, yang mungkin lebih terpengaruh oleh simbol dan gestur politik populis ketimbang evaluasi kebijakan substantif. Ini menunjukkan adanya jurang persepsi antara ruang informasi dan ruang pengalaman rakyat.

Namun, di luar angka-angka itu, rakyat sendiri mulai berbicara. Tanggal 20 Oktober 2025, mahasiswa dan masyarakat dari berbagai elemen berkumpul di sekitar Istana Negara. Mereka membawa sepuluh tuntutan, mulai dari penurunan harga bahan pokok, penghentian perampasan tanah, hingga jaminan kebebasan berpendapat. Ini bukan sekadar aksi protes tahunan, tetapi manifestasi keresahan yang tidak tercermin dalam survei. Demonstrasi itu adalah bentuk koreksi moral terhadap pemerintahan yang terlalu sibuk membangun citra, tapi lupa mendengarkan suara rakyat yang sesungguhnya.
Kritik terhadap kekuasaan adalah bagian dari napas demokrasi. Tapi yang mengkhawatirkan, dalam setahun terakhir, ruang kritik justru makin sempit. Kebijakan yang menyentuh isu lingkungan, tanah, dan industrialisasi sering kali direspons dengan pendekatan koersif mulai dari pembungkaman aktivis hingga kriminalisasi massa aksi. Maka ketika hasil survei menunjukkan angka kepuasan tinggi, pertanyaan yang seharusnya muncul bukan “berapa banyak yang puas,” melainkan “siapa yang berani bersuara?” Karena kepuasan yang tumbuh di bawah tekanan bukanlah cerminan legitimasi, melainkan tanda ketakutan.
Kita tidak menolak survei, tapi kita menolak menjadikannya alat pembenaran kekuasaan. Survei seharusnya menjadi refleksi, bukan dekorasi politik. Pemerintah perlu membaca data bukan untuk berbangga, tetapi untuk mengoreksi arah. Karena yang dibutuhkan rakyat hari ini bukan sekadar angka kepuasan, melainkan keberpihakan yang nyata: menurunkan harga, membuka lapangan kerja, memperkuat perlindungan sosial, dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada rakyat kecil, bukan pada pemodal besar.
Kepuasan publik yang sejati tidak lahir dari survei, melainkan dari rasa aman dan adil di kehidupan sehari-hari. Dari tanah yang tidak dirampas, dari ruang berekspresi yang tidak dibungkam, dari harga kebutuhan pokok yang bisa dijangkau oleh buruh dan petani. Karena itu, angka tinggi dalam survei bukan tanda akhir dari kerja pemerintah, tetapi cermin untuk melihat seberapa jauh mereka telah berpihak pada nurani rakyat. Dan hari ini, nurani itu masih berkata tegas “Angka bisa tinggi, tapi keadilan belum tegak.”